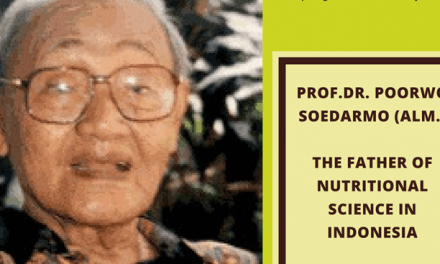Zaman baheula tomat dari kebun di Lembang tiba di Keraton Pakubuwono Kartosuro dalam keadaan busuk-busuk. Begitu juga kol disinggahi ulat-ulat. Ini bukan subversi iblis. Ini masalah infrastruktur. Belum ada jalan yang mulus menghubungkan tanah Sunda—yang dalam metafora M.A.W. Brouwer adalah Tuhan mencipta Tanah Sunda dalam keadaan senyum sehingga hasilnya ‘gemah ripah repeh rapih’—dengan tanah Jawa.
Menyadari terjadi kerugian yang menyulitkan ketenangan hati akan salahsatu dari piranti-piranti infrastruktur di sini, maka si tanganbesi anthek Prancis, Herman Daendels—yang potret dirinya ditampilkan sangat pede, dilukis dengan bagus oleh Raden Saleh, dan karya seni ini sekarang dipajang di dinding Rijksmuseum Amsterdam—susah-susah membikin kerja rodi untuk membangun infrastruktur, khususnya di kasad ini adalah ‘jalan pos’, yang menghubungkan daerah Banten di ujung Jawa Barat ke daerah Osing di ujung Jawa Timur. Lebih kurang jaraknya 1000 km.

Lukisan Herman Willem Daendels, Karya Raden Saleh, 1838. Sumber: howlingpixel.com
Kerja rodi tersebut dikecam dalam sejarah Indonesia, karena bekal sentimen dua alasan berkaitan, antara kemanusiaan di satu sisi dan kebangsaan di sisi lain. Padahal dasarnya hal itu meragukan karena jangan-jangan itu suatu pretensi pathos politik yang curang terhadap realitas hasil pembangunan infrastruktur. Soalnya, lumayan kentara yang diangkat hanya penajaman kontradiksi yang lumrah dalam diskusi perbedaan pendapat menyangkut kerja keras dan pembangunan tersebut.
Namun, bahwa kerja paksa, zonder upah, rodi, memang otomatis menelan banyak korban. Manusia di zaman Daendles itu disimpulkan tersia-sia, terlunta-lunta, bagai jerangkong dibalut kulit keriput tabembeng, tiada lagi masa depan, hanya dianggap sampah kotor.
Jangan lupa, kata ‘rodi’ sendiri berasal dari bahasa Prancis ordure, artinya kotor seperti sampah: sebutan tuan-tuan Prancis di bawah Daendels yang pernah menjajah Indonesia, untuk menggambarkan kuli-kuli kerja paksa. Istilah kaum jelata saat itu untuk kerja rodi di dalam hutan disebut blandong. Sedang Istilah yang dipakai oleh Daendels dengan kritik keras dari bawahan-bawahannya adalah herendiensten, dinas para tuan.

Kerja paksa (rodi) pada masa kolonial Belanda (foto dok. Ist)
Tapi, rupanya resiko dipekerjakan secara paksa dengan nasi sekepal yang diatur Belanda, merupakan padahan teoritis dari realitas pembangunan fisik demi kejayaan masa depan penjajahan. Karuan berlaku aksioma: ada keringat dan airmata, ada pula sukacita dan ketawa riang. Tentu saja ini tidak sama dengan pembangunan jalan tol yang dikerjakan oleh Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono di zaman Presiden Jokowi.
Makanya lewat diktum ini, dalam masa sekarang, ada pertanyaan serius yang kiranya perlu ditanggapi dengan tenang dan cendekia: Siapakah di antara kita yang mengaku diri sebagai bangsa Indonesia bangsa besar, yang sempat berpikir pintar bahwa taroklah misalnya pembangunan Candi Borobudur di zaman pemerintahan Raja Syailendra pada abad ke-8 itu, yang elok dan perkasa—dan yang notabene bolakbalik dilukis dengan angel yang sama melulu oleh Srihadi Soedarsono dengan harga ratusan juta rupiah dalam lelang Heritage Fine Art Auction itu—dulukala telah memakan korban mati bergelimpangan sebagai rodi-rodi? Masuk akalkah kebesaran Candi Borobudur dibangun tanpa derita?!
Narasi sejarah tidak dibaca demikian. Berbeda dengan deskripsi terhadap pembangunan jalan pos Daendles yang dilatari oleh prasangka SARA, dan celakanya prasangka itu kelihatan dipakai kembali di zaman sekarang terhadap hasil kerja Jokowi yang menugaskan Basuki membangun jalan tol antara Jawa Barat dengan Jawa Timur. Makanya deskripsi yang laras dengan realitas itu sekarang adalah ibarat kambing mengembik melihat harimau mengaum.
Kalau pertanyaan ini kita sampaikan kepada tukang bajigur atau bahkan pokrolbambu, niscaya jawabnya meleset plungkar-plungker membikin sakit gigi. Coba tanya itu kepada misalnya John Stuart Mill—bukunya Principles of Political Economy—atau kepada William James—bukunya The Principles of Psychological—serta kepada David Hume—bukunya Enquiring Concerning the Principles of Morals. Orang-orang pandai ini dikenal sebagai pemikir filsafat yang mengurai hubungan-hubungan metafisis, estetis, etis dan logis dari jangkauan landas psikologis. Ladangnya lazim disebut widya psikologisme.

Foto: Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat meresmikan Toll Trans Jawa di Ngawi, Jawa Tengah (20/12/2018, sumber: majalahagraria.com/Dok. Ist.)
Di luar itu memang pengetahuan ini diejek di Jerman oleh Edmund Husserl—bukunya Logische Untersuchungen—investigasi logika, dan disebutnya sebagai ‘psichologis mus‘. Bahwa di situ pandangan dasar psikologi dibilang telah dibawa lebih keluar di wilayah filsafat, di mana dengannya malah menyepelekan jurus epistemologi menyangkut nilai logikanya.
Dalam pada itu, kalau disorot lebih khusus ke widya psikososial atau psikologi sosial, sertamerta dapat ditemukan jawaban tahkik yang tidak harus mengejutkan, bahwa boleh gerangan diterima konklusi yang menganggap: niscaya ada derita, kesusahpayahan, kepedihperihan dalam suatu pembangunan projek besar karya agung Candi Borobudur itu. Demikian arahannya di konteks sekarang. Bahwa lumrah berlangsung kerja-kerja keras infrastruktur: meliputi kaitan ladang-ladang politik, sosial, ekonomi, budaya, agama—yaitu semuanya yang sudah dan sedang ditangani oleh bekas walikota Solo yang atas pilihan rakyat lantas menjadi gubernur Jakarta dan atas pilihan rakyat lagi lantas menjadi presiden RI.
Gampangnya, dalam pandangan rakyat secara am, melihat secara kasatmata akan terbentangnya jalanraya-jalanraya di banyak pulau yang menghubung-hubungkan satu tempat dengan tempat lain. Bagi rakyat am tersebut, bagian perdana infrastruktur adalah jalan-jalan tersebut—aspal untuk ban karet dan besi untuk roda besi—hal yang membuat rakyat itu plong, karena bisa mencapai dengan lancar memakai kendaraan-kendaraan bermotor buatan Jepang, Korea, Cina, yang bisa dibeli dengan cara cicil: sehingga pembelinya pun pecicilan.
Namun, dengan kendaraan bermotor itu, yang ditunjang dengan jalan aspal sistem hotmix, maka yakin tomat dari kebun di Kabanjahe pun, menyeberangi dua laut: Selat Sunda dan Selat Bali, tiba di Denpasar belum busuk.
Padahal barangkali jalanan hotmix yang dimanfaatkannya tak sedikit diberi halangan-halangan untuk mengurangi kecepatan. Ini hobi orang Indonesia yang hidup di dunia modern, tapi dengan sukrela ditawan tradisi kampung yang bisa juga jadi kampungan. Sebab, agar kendaraan bermotor itu benar memelankan lajunya, dipasanglah di tengah-tengahnya suatu ‘kuburan ular’ yang populernya disebut ‘polisi tidur’.

Koleksi Departemen Keuangan, sumber: depkeu.go.id
Biasanya di bagian-bagian padat jalanan di Jakarta yang ada kuburan ular itu, dipasang juga tulisan ancaman sangar berbunyi ‘ngebut benjut’. Jadi kalau ada orang yang ngebut di situ bisa-bisa orang-orang se-RT se-RW bertempik sorak rame-rame bakal ngamuk menghajarnya. Mengerikan. Karuan orang-orang yang selama ini mengenal pujian prototip “bangsa Indonesia bangsa ramah”, mendadak melihatnya dengan fadihat baru “orang Indonesia ngamukan”.
Maka, jangan kaget, entri ‘amuk’ terbaca juga di kamus-kamus bahasa Inggris. Misalnya Dictionary of English Language and Culture, mencatatnya “a desire to kill people.”
Kembali ke cerita ‘jalan pos’ Daendels yang dibangun untuk melipatgandakan pendapatan pemerintah. Manakala abad berganti bersamaan dengan tantangan ekonomi makin besar, di samping ‘jalan pos’ itu, pada 1884 dibangun rel untuk Si Gombar, sebutan khas orang di Bandung kala itu untuk keretaapi.
Iklan keretaapi agar merangsang penumpang untuk naik keretaapi berbunyi begini: “Ten tijde van G.G. Daendels, reisde men met snellepostpaarden van Bandoeng naar Batavia in 2¾ dag. Thans met de Vlugge Vier in 2¾ uur.” Artinya, “Di zaman gubernur jenderal Daendels perjalanan paling cepat dari Bandung ke Jakarta memakan waktu 2¾ hari. Sekarang dengan Vlugge Vier hanya memakan 2¾ jam. Vlugge Vier, artinya ’empat cepat’, sebutan untuk keretaapi milik perusahaan, Staats Spoorwagen, Keretaapi Negara, berasal dari singkatan SSSS yaitu Staats Spoor Steeds Sneller, artinya Keretaapi Negara Lebih Cepat.

Foto Tantowi Yahya, sumber: youtube.com
Senangnya orang di Jawa waktu itu, dengan kantor pusat keretaapi di Bandung, bahwa penataan infrastruktur dalam memajukan negeri koloni ini, menyebabkan sejak abad ke-19 penduduknya sudah kulina ‘numpak sepur’, naik keretaapi. Yang kasihan orang-orang di pulau-pulau lain di Indonesia bagian timur bahkan belum pernah lihat keretaapi sampai di abad ke-21. Orang di sana baru akan ‘numpak sepur’ di zaman pemerintahan Jokowi.
Sepuluh tahun pemerintah SBY yang menonjol adalah karyanya berupa lagu-lagu pop. Hal itu dicela dengan kata-kata cemar oleh Prof Dr Tjipta Lesmana di Metro TV pada 15 Oktober 2010 jam 19:45. Sementara , dua di antara lagu pop SBY malah cenderung dianggap plagiarisme.
Kedua lagu itu disejajarkan dengan “When a girl in your arms” nyanyian asli Cliff Richard dari hit 1960-an, dan bagian refrain “Baby blue” nyanyian George Baker dan versa “Island in the stream” lagu Bee Gees yang dinyanyikan Kenny Rogers berduet dengan Dolly Parton dari hit 1970-an. Untuk lagu yang disebut ini SBY membayar Tantowi Yahya mengaransemen kemudian menyanyikannya secara country.
Di luar itu, karena belum ada keretaapi di Sulawesi pada 1970 sampai era pemerintahan SBY, maka seorang perempuan bernama Ermy Kullit, pada tahun-tahun belakangan ini dikenal sebagai penyanyi Jazz tapi bakatnya terbatas dan tidak seronok seperti artis-artis umumnya, tampak terheran-heran ketika pertama kali naik keretaapi pada 1973. Dia bertanya kepada saya, “Ini oto apa namanya?” Jawab saya, “Ini bukan oto, namanya keretaapi.” Dia bertanya, “Memangnya keretaapi berjalan dengan cara merayap begitu?” Dan saya bergurau menjawabnya, “Kalau ingin lebih cepat keretaapi bukan merayap memanjang, tapi menegak meninggi.” Dia percaya. Waktu itu dia baru pertama kali ke Jawa, dan kami naik keretaapi dari Jakarta ke Bandung. Wong ndeso tenan.

Ermy Kulit, Maestro Jazz Indonesia (sumber: pesona.com)
Sekarang orang-orang di Minahasa, kampunghalaman Ermy Kullit yang mayoritas Nasrani itu, bisa melafas “haleluyah”, sebab di zaman pemerintahan Presiden Jokowi, konon sedang dibangun jalan keretaapi di sana. Adapun pesaing Jokowi di pemilu 2019, Prabowo yang mengaku berdarah Minahasa, belum sempat membangun jalanan keretaapi di sana, antaralain tak berhasil menang dalam pemilu tahun ini sehingga tak jadi memakai sedan hitam bernomor RI 1.***